
Cara membaca pikiran orang juga sering disebut komunikasi empatik. Biasanya, istilah itu diartikan sebagai membaca pikiran orang lain. Walaupun sebenarnya yang kita baca adalah pikiran kita sendiri. Kita membaca pikiran orang lain melalui pikiran kita sendiri.
Tidak ada yang kita baca selain pikiran kita sendiri di dunia ini. Segala sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, kita baca, kita pahami itu melalui pikiran kita sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang datang begitu saja tanpa melalui saringan di kepala kita yang kita kenal sebagai jaringan otak. Dan pasangannya di alam nir-ruang dan waktu kita sebut sebagai pikiran atau mind.
Pertanyaannya adalah: Bagaimana cara membaca pikiran orang lain melalui pikiran kita sendiri?
Jawabannya mudah saja. Kita harus mulai dari awal kembali, membayangkan ketika pertama kali kita mengenal yang disebut kesadaran. Apakah yang pertama kita sadari itu? Bukankah pertama kali kita sadar dan mengenali diri kita setelah beberapa saat terlahir di dunia ini? Bukankah pertama kali yang kita sadari (kenali) adalah orang lain (ibu, ayah, dan lingkungan)?
Sebagai bayi, kita menyadari diri kita sebagai orang lain, terutama sebagai ibu kita. Atau lebih tepatnya, kita sebagai bagian dari ibu kita. Tidak ada yang namanya “ego” itu selain kebutuhan-kebutuhan fisikal yang dirasakan oleh kita sebagai bayi. Selanjutnya, segalanya adalah ibu kita, dan kita sebagai bagian dari ibu. Dan apa pun yang dirasakan ibu kita akan kita rasakan: emosi-emosinya, kegalauannya, kegembiraannya.
Setelah itu kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita: ayah, saudara-saudari, lingkungan, walaupun saat itu kita masih seorang bayi yang belum bisa berkomunikasi dengan kata-kata. Kita sadar bahwa kita sadar, tetapi kesadaran kita adalah kesadaran orang lain. Kesadaran yang ada di manusia-manusia dewasa yang berada di sekitar kita.
Seiring waktu, sedikit demi sedikit lingkungan akan mengajarkan bahwa kita beda, bahwa kita adalah entitas yang berdiri sendiri. Sebagai manusia modern, inilah sosialisasi yang kita alami, walaupun kita juga menyadari bahwa banyak manusia yang budayanya primitif tetap mengalami identitas komunal sepanjang hidupnya.
Sebagai manusia modern kita akhirnya dibiasakan untuk berpikir bagi diri kita sendiri, menyatakan kebutuhan kita, mengartikulasikan kepentingan kita. Dan lahirlah “ego”. Ego adalah kita, vis a vis orang-orang lain. Tetapi ego adalah perkembangan lanjutan dari diri kita yang asli ketika lahir di dunia ini. Kita lahir tanpa ego. Ego adalah bentukan budaya, superficial.
Setelah kita dewasa, kita akan terbiasa untuk berpikir dalam konteks “kita vs mereka”. Yang kita lihat dan kita rasakan hanyalah diri kita sendiri karena kita disosialisasi seperti itu. Tidak ada lagi yang namanya merasakan melalui orang-orang lain karena kita tahu bahwa setelah tahap bayi berlalu, kita harus menghadapi orang-orang lain sebagai orang lain: Orang lain bukanlah saya dan saya mesti menyatakan minat-minat saya yang berbeda dengan minat orang lain.
Kepentingan saya sebagai entitas tersendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang terpisah dari kepentingan orang-orang lain: baik orang dekat, orang jauh, lingkungan dekat, lingkungan jauh, masyarakat, maupun dunia luas. Empati masih ada, karena kita masih bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang lain itu, kalau kita mau. Tetapi, itu “tidak normal”. Yang dianggap normal adalah dipertahankannya mode saya versus orang lain tersebut.
Saya selalu mengatakan bahwa komunikasi empatik adalah bakat alam dari tiap orang. Artinya, komunikasi empatik adalah sesuatu yang telah kita miliki sebagai mode awal dari interaksi kita sebagai manusia ketika terlahir ke dunia, yang telah kita lakukan dengan fasih ketika kita masih bayi dan belum bisa berkata-kata. Komunikasi telah mendarah daging ketika segala konsep tentang kepentingan diri sendiri belum ditanamkan ke diri kita oleh lingkungan budaya tempat kita dibesarkan.
Susahnya adalah menguraikan benang kusut antara “saya” dan “mereka”, antara impresi-impresi (kesan-kesan) yang masuk ke dalam pikiran saya. Impresi-impresi itu tetap sebagai impresi dan selalu ada di pikiran saya, tetapi saya kesulitan membedakan impresi itu mengenai saya atau orang lain. Yang menghalangi tentu saja ego saya yang merupakan konsep diri saya yang ditanamkan oleh budaya tempat saya dibesarkan. Saya dan Anda dibesarkan dengan pengertian bahwa ego harus dipertahankan demi kewarasan pikiran. Kalau tidak, maka kita bisa terombang-ambing antara kepentingan saya dan kepentingan orang lain yang saya lihat sebagai saya juga.
Memang benar akan ada kemungkinan seperti itu, terutama bagi mereka yang lemah mental. Tetapi di sini saya akan berbicara tentang hal-hal yang umum dan berlaku bagi semua orang. Bukan tentang psikologi klinis yang menyelidiki skizofrenia, paranoia, dan sebagainya. Ada orang yang lemah mentalnya dan tidak bisa melakukan komunikasi empatik tanpa jatuh ke dalam kategori tidak waras dan ada juga orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan komunikasi empatik sebagaimana komunikasi umumnya, yang apa adanya dan tanpa dipaksakan.
Secara gamblang, komunikasi empatik adalah mengomunikasikan sesuatu yang kita baca dengan pikiran kita tentang yang dirasakan orang lain, aspirasinya, ketakutannya, kepentingannya. Dan itu bisa kita lakukan apabila kita mau kembali menelaah situasi yang terjadi ketika kita masih bayi sebelum konsep ego ditanamkan oleh lingkungan kita. Kita akan bisa melihat orang lain seperti kita melihat diri kita sendiri. Kita akan bisa merasakan orang lain seperti kita merasakan diri kita sendiri.
Tetapi ada bedanya dibandingkan dengan ketika kita masih bayi dan belum bisa menerangkan tentang yang kita lihat dan rasakan mengenai orang-orang lain. Sekarang, kita akan bisa membedakan bahwa sesuatu yang kita lihat itu adalah mengenai orang lain: the others. Bukan kita sebagai diri kita yang merupakan entitas terpisah dari orang-orang lain itu. Ketika kita masih bayi, hal itu tidak bisa kita lakukan.
Anda bisa mencobanya saat ini juga. Cobalah untuk berpikir dan merasakan seolah-olah Anda adalah orang lain: teman akrab Anda, pasangan Anda, saudara Anda, saudari Anda tetangga Anda, atau siapa pun. Ucapkanlah, tuliskanlah, cobalah dicocokkan dengan orangnya. Dengan begitu Anda telah melakukan komunikasi empatik!
Di bagian atas telah saya tuliskan bahwa tahap pertama dalam penguasaan komunikasi empatik adalah dengan mencoba membayangkan diri kita sendiri sebagai orang lain. Seolah-olah kita adalah orang lain itu. Caranya memang mudah, dan bahkan tahap-tahap selanjutnya juga sama mudahnya.
Tahap berikutnya dijalankan dengan melakukan osmosis. Osmosis adalah istilah ilmu alam yang berarti menyamakan isi dari sesuatu yang kosong dengan sesuatu yang berisi. Kalau saya selembar kertas kosong, dan di sebelah saya ada selembar kertas lain yang berisi tulisan-tulisan, maka isi kertas itu bisa berpindah ke kertas kosong di sebelahnya.
Maksud istilah itu adalah, penyerapan pengetahuan dari seseorang tanpa melalui cara-cara umum; tanpa perlu diajari secara formal, walaupun tetap harus ada komunikasi intensif. Cara melakukan osmosis bukanlah sesuatu yang aneh bagi kita manusia-manusia normal, karena kita sudah melakukan osmosis itu sepanjang hidup kita.
Bukankah kita sudah menyerap segala nilai budaya masyarakat kita tanpa merasa mempelajarinya secara sungguh-sungguh: dari orangtua kita, teman, dan semua yang kita temui sepanjang hidup kita? Kita telah melakukannya sejak kita menyadari bahwa kita memiliki kesadaran sebagai sebuah entitas.
Tidak ada cara lain bagi kita dalam mempelajari sesuatu secara mendalam kecuali melakukan osmosis. Osmosis dari dosen-dosen pengajar atau penulis yang kita kagumi. Segala teknik yang dipelajari itu cuma pengisi waktu saja, sebagai bukti empirik bahwa ada metode yang diajarkan dan dipelajari. Tetapi untuk bisa dan memahami mau tidak mau kita harus melakukan osmosis.
Setelah osmosis kita jalankan, dengan mudah kita akan bisa mengembangkan teknik kita sendiri, bahkan pengertian kita sendiri.
Mungkin apa yang saya tulis kali ini terasa mengejutkan bagi sebagian rekan. Mungkin juga ada sebagian rekan yang telah bisa meraba secara intuitif bahwa pada akhirnya saya akan menuliskan hal ini juga, apa pun konsekuensinya.
Pertama, seperti disebutkan sebelumnya, kita bisa memulai komunikasi empatik dengan cara membayangkan diri kita sebagai orang lain itu: teman, pasangan hidup, atasan, bawahan, kolega bisnis, dsb. Dan kedua, dengan mulai melakukan osmosis dari orang-orang yang kita anggap telah mahir melakukan komunikasi empatik.
Segala percakapan dengan menggunakan bahasa sehari-hari adalah komunikasi yang empatik dengan aliran-aliran osmosis dari alam bawah sadar orang yang satu ke bawah sadar orang yang satunya lagi, dan bergerak kembali dengan input, output, dan feedback yang tidak berkesudahan. Hasil akhirnya adalah pemenuhan isi dari seseorang yang tidak memiliki dengan isi dari orang yang memiliki. Osmosis selalu berlangsung dua arah.
Nah, bukankah osmosis ini sesuatu yang natural bagi kita? Kita telah melakukannya sepanjang hidup kita. Waktu kuliah, kita bisa menangkap maksud hati seorang dosen hanya dengan mengamatinya. Waktu masih pacaran, kita bisa tahu bahwa pacar kita serius atau tidak dalam berhubungan dengan kita. Setelah menikah, kita bahkan bisa tahu kalau pasangan kita hanya mempertahankan formalitas belaka karena segala desir romantik telah habis terpakai.
Jadi, komunikasi empatik juga mengandalkan osmosis yang tidak berkesudahan antara kita dan orang-orang yang kita ajak berkomunikasi. Kalau Anda merasa perlu melakukan osmosis dari saya, that’s fine too. Aturlah waktu untuk bertemu saya atau saling berkirim e-mail dan SMS! Bisa juga melalui chatting atau bahkan cukup dengan hanya membaca tulisan-tulisan saya.
Sesederhana itu. Tetapi, tentu saja masih banyak lagi pernak-perniknya. Sekali bertemu saja tidak cukup, sekali membaca saja juga tidak cukup. Anda perlu bertemu atau membaca berulang-ulang untuk bisa menangkap esensi komunikasi itu.



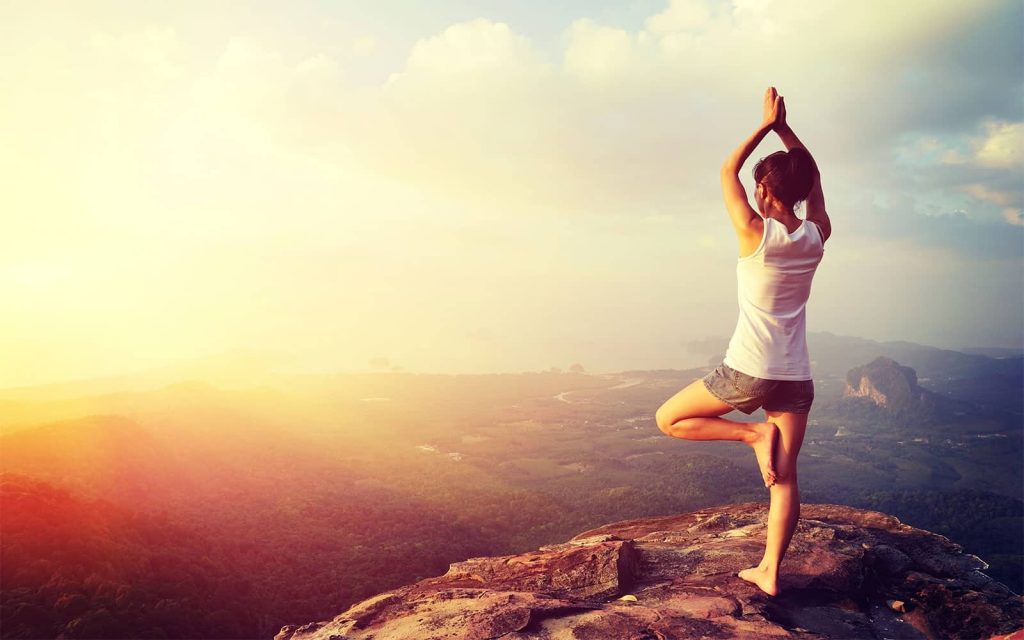

owh jadi bisa pakai komunikasi empatik yah